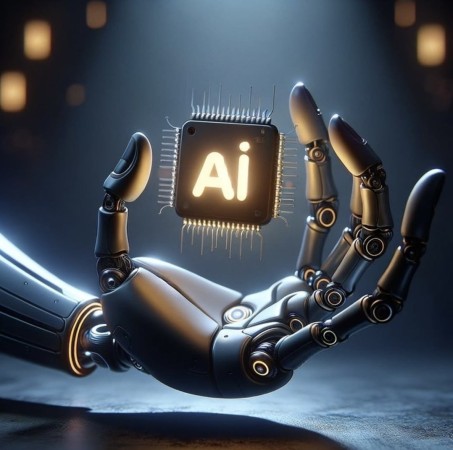Oleh: Fabian Alfarizi, NIM: 251552010039, mahasiswa STMIK Tazkia, Prodi Teknik Informatika
- Baca Juga Digitalisasi UMKM dan Kesiapan Nyata
Di era ketika semuanya serba cepat, ada satu hal yang justru makin tertinggal: kesehatan mental kita sendiri. Setiap hari kita disuguhi notifikasi, target, komentar, perbandingan, dan tekanan yang muncul begitu saja dari layar kecil di genggaman. Rasanya seperti hidup di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendirian. Lalu muncul pertanyaan besar: kalau teknologi ikut menyumbang masalah, bisakah teknologi juga menjadi bagian dari solusinya?
Menurut saya, jawabannya: bisa. Bahkan sangat bisa—kalau dijalankan dengan empati.
Teknologi Membantu, Tapi Juga Melukai
Fakta yang sering kita lewatkan adalah bahwa masalah kesehatan mental bukan lagi isu kecil. WHO mencatat ratusan juta orang mengalami depresi, dan Indonesia tidak jauh berbeda. Banyak anak muda yang terjebak dalam stres, kecemasan, atau kelelahan mental, tapi merasa takut atau malu mencari bantuan.
Sementara itu, platform digital justru menambah tekanan: konten yang membuat kita membandingkan diri, budaya hustle yang menuntut produktivitas nonstop, serta algoritma yang lebih fokus mengejar engagement daripada kenyamanan pengguna.
Di titik ini, kita butuh pendekatan baru. Kita butuh teknologi yang mengerti manusia.
Di Sini Peran IT Entrepreneurship Menjadi Penting
Sebagian orang berpikir startup hanya soal mengejar profit atau membuat aplikasi viral. Padahal, dunia kewirausahaan teknologi punya potensi besar untuk membuka akses kesehatan mental yang selama ini sulit dijangkau. Ada beberapa alasannya.
1. Teknologi Bisa Menembus Batas yang Tidak Bisa Dijangkau Layanan Konvensional
Platform seperti Riliv, Bicarakan.id, atau Mindtera sudah membuktikan kalau konseling online bisa menjadi penyelamat banyak orang. Tidak perlu datang ke klinik, tidak perlu malu, dan biayanya jauh lebih terjangkau.
Saya melihat ini bukan hanya sebagai perkembangan bisnis, tapi juga langkah kecil yang membuat orang berani mencari bantuan.
2. Algoritma Bisa Menjadi Teman yang Mengingatkan Kita
AI sebenarnya punya kemampuan mendeteksi perubahan emosi kita melalui pola bahasa atau kebiasaan digital. Tentu ini harus dilakukan dengan etika yang ketat, tapi potensinya besar: teknologi bisa memberi tanda awal sebelum kondisi seseorang memburuk.
Bayangkan kalau ponsel kita bisa berkata, “Kamu kelihatan lelah hari ini. Mau istirahat sebentar?”
Terkesan sederhana, tapi bisa menyelamatkan banyak orang.
3. Produk Digital yang Lebih Lembut Bisa Mengurangi Tekanan Hidup
Tidak semua inovasi harus besar. Terkadang, aplikasi yang tidak membombardir notifikasi, desain yang tidak agresif, atau fitur digital detox sederhana saja sudah membantu seseorang merasa lebih tenang.
Startups seperti Calm dan Headspace berangkat dari hal kecil: menghadirkan ruang hening di tengah hiruk pikuk internet. Akhirnya, mereka justru menjadi raksasa.
Intinya: produk yang manusiawi justru lebih dicintai.
Lalu Apa yang Bisa Dilakukan Para Pendiri Startup?
Menurut saya, ada beberapa langkah sederhana tapi krusial:
1. Ajak psikolog, peneliti perilaku, atau konselor untuk terlibat sejak awal.
Produk kesehatan mental tidak bisa hanya mengandalkan insting programmer.
2. Bangun fitur yang menenangkan, bukan membuat kecanduan.
Makin sedikit notifikasi tidak penting, makin baik.
3. Transparan soal data.
Pengguna harus tahu dengan jelas apa yang dikumpulkan dan untuk apa.
4. Jangan hanya mengejar pasar besar—perhatikan kelompok rentan.
Remaja, mahasiswa, pekerja muda, atau orang dari daerah terpencil membutuhkan perhatian lebih.
5. Kolaborasi dengan pemerintah, kampus, dan komunitas.
Menyelesaikan masalah mental tidak bisa sendirian; harus jadi gerakan bersama.
Penutup: Kita Butuh Teknologi yang Mengerti Manusia
Pada akhirnya, kita tidak membutuhkan aplikasi yang “pintar”, tetapi aplikasi yang peduli.
Bukan algoritma yang membuat kita ketagihan, tetapi algoritma yang memahami batas manusia.
Bukan startup yang mengejar perhatian, tetapi startup yang memberi ruang bernapas.
Kalau para pelaku IT entrepreneurship berani mengambil jalan ini—jalan yang mungkin tidak selalu paling menguntungkan dalam jangka pendek—maka teknologi bisa menjadi teman, bukan ancaman.
Dan mungkin, di tengah dunia yang cepat dan bising ini, kita akhirnya bisa merasa sedikit lebih tenang.